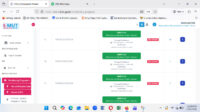TERASKALTARA.ID, MALINAU – Natal berarti kelahiran Sang Juru Selamat. Ia adalah perayaan akan kesederhanaan. Dalam pusaran waktu, ia kerap kehilangan denyut makna spiritualnya. Di tengah gemerlap lampu yang menyilaukan, pesta yang riuh, dan hiruk-pikuk belanja tanpa henti, esensi kesederhanaan yang dahulu menjadi napas peristiwa kudus ini perlahan terkikis. konsumerisme telah menodai kesuciannya, dan menjadikannya sekadar panggung unjuk kemewahan dan ajang unjuk gengsi.
Perayaan yang seharusnya menumbuhkan kasih, pengharapan dan kedamaian, sering tereduksi menjadi rutinitas seremonial tanpa jiwa. Di balik tumpukan makanan dan pesta megah, makna sejati tentang pengorbanan dan cinta yang tulus seolah tenggelam. Natal bukan lagi tentang palungan sederhana di Betlehem, melainkan tentang siapa yang paling bersinar di tengah pesta dunia.
Namun, di antara riuhnya dunia yang kian materialistis, masih ada ruang bagi jiwa-jiwa yang ingin kembali pada makna sejati Natal. Sebuah panggilan untuk meneladani kasih yang lahir dalam kesederhanaan, untuk berbagi tanpa pamrih, dan untuk menemukan kembali damai yang melampaui segala kemewahan duniawi.
Kehidupan modern telah menjadi panggung besar bagi hasrat yang tak pernah puas. Dorongan untuk memiliki lebih banyak, membeli lebih sering, dan menampilkan kemakmuran sebagai simbol keberhasilan telah menjelma menjadi liturgi baru zaman ini. Seperti dikatakan oleh teolog Jürgen Moltmann, manusia modern “tidak lagi menantikan keselamatan, melainkan memeroduksinya dalam bentuk barang.” Dalam pusaran konsumerisme, nilai-nilai spiritual perlahan terkikis, digantikan oleh logika pasar yang menilai manusia bukan dari kedalaman jiwanya, melainkan dari daya belinya.
Budaya konsumtif ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan krisis teologis dan antropologis. Walter Brueggemann menulis bahwa masyarakat modern hidup dalam “narasi kelangkaan,” di mana rasa cukup dianggap kegagalan, dan kekayaan menjadi satu-satunya bentuk keselamatan yang diakui. Akibatnya, manusia kehilangan kemampuan untuk bersyukur dan berbelas kasih. Alam dieksploitasi, sesama diabaikan, dan jiwa menjadi kering di tengah limpahan materi.
Paradoks ini mencapai puncaknya, ketika perayaan yang seharusnya menjadi momen kontemplasi atas kasih yang turun ke dunia, justru berubah menjadi festival konsumsi. Pusat perbelanjaan menjadi “katedral” baru, iklan menjadi “khotbah” yang menggoda, dan kasih digantikan oleh transaksi. Seperti diingatkan oleh teolog Henri Nouwen, “kita telah kehilangan keheningan yang memungkinkan kita mendengar suara lembut Allah di tengah hiruk-pikuk dunia.” Natal pun berisiko menjadi sekadar pesta tanpa makna, kehilangan roh inkarnasi yang sejatinya mengajarkan kerendahan hati, solidaritas, dan cinta yang memberi tanpa pamrih.
Natal yang dahulu berakar pada doa, kebersamaan, dan rasa syukur kini perlahan kehilangan makna sejatinya. Di tengah gemerlap lampu dan hiruk-pikuk pesta, manusia modern kerap terjebak dalam euforia lahiriah yang menutupi keheningan batin. Hadiah, dekorasi, dan busana baru menjadi pusat perhatian, sementara hati yang seharusnya menjadi palungan bagi Sang Damai justru dibiarkan kosong.
Perayaan yang semestinya menjadi perwujudan kerendahan hati kini menjelma menjadi panggung kompetisi sosial—siapa yang paling mewah, siapa yang paling berkilau. Dalam pusaran ini, pesan Natal tentang kasih tanpa pamrih dan solidaritas terhadap sesama memudar, seperti cahaya lilin yang tertiup angin kesombongan dan keserakahan.
Teolog Katolik Karl Rahner pernah menulis, “Natal bukanlah sekadar peringatan kelahiran Kristus di Betlehem, melainkan kesediaan hati manusia untuk menjadi tempat kelahiran Allah di dunia.” Pernyataan ini menegaskan bahwa inti Natal bukan pada perayaan luar, melainkan pada transformasi batin—pada keberanian untuk membuka diri terhadap kasih yang melampaui batas-batas ego.
Kesederhanaan bukan sekadar perkara hidup dengan sedikit, melainkan seni menemukan kecukupan dalam setiap helaan napas. Gaya hidup ugahari menuntun manusia untuk menimbang dengan jernih antara kebutuhan dan keinginan, antara hasrat untuk memiliki dan panggilan untuk berbagi. Di tengah derasnya arus globalisasi dan gemerlap dunia digital, nilai luhur ini kian tergerus oleh budaya pamer dan keinginan tanpa batas. Ironisnya, Natal—yang sejatinya menjadi ruang hening untuk meneguhkan kembali makna syukur dan kesederhanaan—sering kali berubah menjadi panggung konsumerisme, di mana makna rohani tergantikan oleh hiruk-pikuk belanja dan simbol kemewahan.
Kesederhanaan bukan sekadar sikap menahan diri dari kemewahan, melainkan panggilan untuk hidup dalam harmoni dengan seluruh ciptaan. Dalam terang iman Katolik, kesederhanaan adalah bentuk partisipasi manusia dalam karya penciptaan Allah yang terus berlangsung. Santo Fransiskus dari Assisi, pelindung ekologis Gereja, mengajarkan bahwa “segala makhluk adalah saudara dan saudari kita,” karena semuanya berasal dari kasih yang sama. Maka, kesadaran ekologis bukanlah tren modern, melainkan ekspresi iman yang mendalam terhadap Sang Pencipta.
Natal menjadi saat yang tepat untuk memperbarui relasi kita dengan bumi yang telah lama terluka oleh keserakahan dan ketidakpedulian. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si’ menegaskan bahwa “tidak ada ekologi tanpa antropologi yang benar,” sebab krisis lingkungan berakar pada krisis moral manusia. Dengan demikian, tindakan sederhana seperti mengurangi limbah, memilih hadiah yang berkelanjutan, dan merayakan tanpa berlebihan adalah wujud nyata kasih terhadap ciptaan—kasih yang meneladani Kristus yang lahir dalam kesederhanaan palungan.
Lebih dari itu, kesederhanaan membuka ruang bagi empati dan solidaritas. Dalam keheningan yang bebas dari hiruk-pikuk konsumsi, hati manusia menjadi lebih peka terhadap penderitaan sesama. Santo Yohanes Paulus II pernah menulis, “manusia menemukan dirinya sendiri ketika ia dengan tulus memberikan diri kepada orang lain.” Maka, berbagi dalam semangat Natal bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang menghadirkan diri—memberi waktu, perhatian, dan kasih yang tulus. Dalam kesederhanaan itulah, makna sejati Natal bersinar paling terang.
Untuk menemukan kembali makna sejati Natal, perlu ada keberanian untuk melawan arus konsumerisme. Natal bukan tentang seberapa megah perayaannya, tetapi seberapa tulus kasih yang dibagikan. Kesederhanaan menjadi jalan untuk menemukan kedamaian batin dan keutuhan relasi dengan sesama. Dengan hidup sederhana, manusia belajar untuk bersyukur, berbagi, dan menghargai hal-hal kecil yang bermakna. Inilah makna Natal sesungguhnya. Selamat Natal untukmu semua yang merayakannya.
Oleh : Dr. Markus Maluku, S.Fil., M.Pd.